Jakarta — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Kemendikbud Ristek menyatakan, aturan tersebut guna memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
“Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal kita untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi kita,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11).
Keberadaan aturan tersebut dinilai Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) penting di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Seperti dialami mahasiswi yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual seorang dosen di Universitas Riau (Unri) yang sedang viral di media sosial. Pihak rektorat langsung membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus itu.
Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi UNRI itu pun diapresiasi Komnas Perempuan. Harapannya, selain proses di internal kampus, kehadiran Permendikbud 30/2021 menjadi membuat kasus pelecehan seksual di kampus seperti dialami mahasiswa di Riau dapat ditindaklanjuti.
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, pada dasarnya aturan itu untuk mewujudkan kampus yang aman, sehat, dan nyaman dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terutama kekerasan seksual. Hal ini seturut dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Komnas Perempuan mengajak seluruh pihak untuk mengawal dan memastikan Permendikbud dilaksanakan dan mencapai tujuannya untuk mencegah, menangani dan memulihkan korban kekerasan seksual,” kata Siti, Rabu (10/11).
Meski dianggap baik, sejumlah kalangan menilai berbeda. Oleh sebagian orang, frasa ‘tanpa persetujuan’ korban dianggap mempersulit korban memperoleh keadilan. Bahkan, aturan itu juga dinilai melegalkan zina.
Siti menilai Permendikbud tersebut justru memperkuat posisi korban. Dia menjelaskan yang dimaksud pasal 5 ayat 2 pada Permendikbud tersebut adalah jika korban ‘memberikan persetujuan’ atas tindakan-tindakan kekerasan sesku dalam kondisi mabuk atau tidak dalam kondisi tidak penuh kesadaran karena alkohol atau obat-obatan atau narkoba, maka persetujuannya tersebut tidak sah. Tindakan pelaku yang lantas memanfaatkan kondisi korban itulah, katanya, tetap tidak bisa dimaafkan. Harus disanksi.
“Ini memperkuat posisi korban bahwa kondisi kerentanan dan ketidakberdayaan korban, tidak boleh dijadikan alasan bahwa aktivitas seksual dilakukan atas dasar suka sama suka,” ujar dia.
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, juga merasa janggal ketika aturan itu dikaitkan dengan melegalkan zina. Dia menganggap, sejumlah narasi yang menolak terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di ranah kampus justru dapat berpotensi menyerang korban.
“Narasi penolakan aturan ini justru berpotensi menyerang korban. Dengan mendasarkan kekerasan seksual pada aspek adanya perkawinan/sesuai norma, korban akan sulit memperoleh keadilan karena akan distigma terlibat dalam hubungan tidak legal, moralitasnya akan digali, korban akan dikotak-kotakan dan terus direndahkan ketika melaporkan kasusnya, ketimbang memberikan ruang aman bagi korban,” kata Maidina dalam keterangannya, Kamis (11/11).
Padahal berdasarkan survei Kemendikbud 2020, lanjut Maidina terdapat 63 persen korban kekerasan seksual di kampus tidak melaporkan kasusnya kepada pihak kampus karena minimnya ruang aman bagi korban. Hal inilah yang justru ingin diselesaikan dengan keberadaan Permendikbud ini.
Pada prinsipnya mendasarkan kekerasan seksual pada ketiadaan consent atau persetujuan, menurut Maidina sama dengan memberikan ruang aman bagi korban manapun. Meskipun pada prinsipnya korban seharusnya tidak dinilai berdasarkan pemenuhan dirinya terhadap norma-norma yang ada, namun selama ini hal tersebut menjadi penghalang utama seseorang dapat disebut sebagai ‘korban’.
“Padahal, penyematan dan pengkategorian sebagai ‘korban’ menjadi sangat penting di dalam sistem perlindungan di Indonesia,” ujar dia.
Maidina berpendapat bahwa Permendikbud ini telah tepat dalam memasukkan elemen persetujuan ke dalam definisi kekerasan seksual. Tanpa adanya elemen persetujuan, sistem yang telah dibangun tidak akan dapat dijalankan, dikarenakan korban akan terlebih dahulu ‘dihakimi’ berdasarkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan norma, juga bias terhadap relasi kuasa yang ada.
“Langkah yang diambil oleh Kemenristekdikti dan Kemenag sudahlah tepat. Aturan-aturan ini harus terus didukung,” tandasnya. (*)





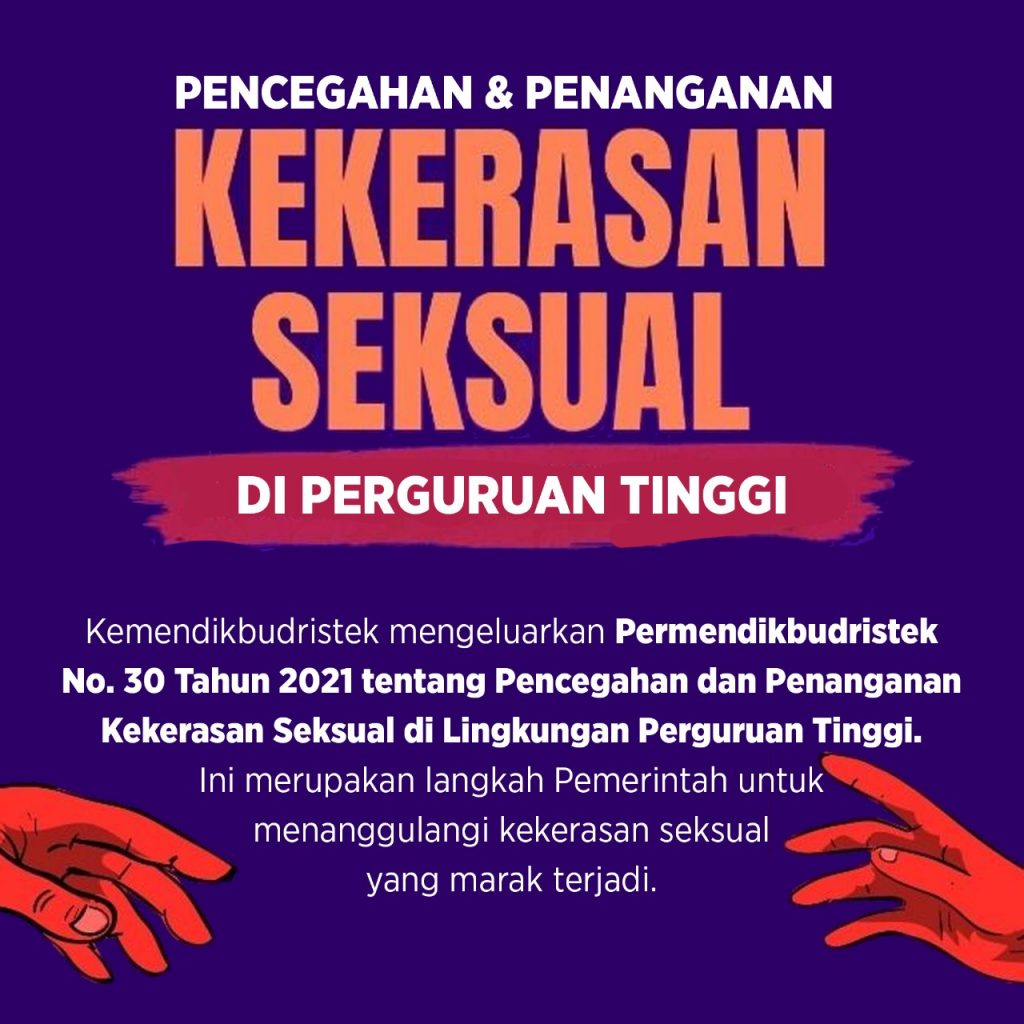




More Stories
Stabilitas Pasokan Beras Nasional: Peninjauan Jokowi dan Zulhas ke Gudang Bulog Karawang
Catatan Ketua Melanesian Youth Forum, Steve R. Mara Menanggapi Keputusan MSG terhadap ULMWP
Pengakuan mengejutkan, Ricky Pagawak Sebut Transfer Sejumlah Uang Kepada Kapolda papua